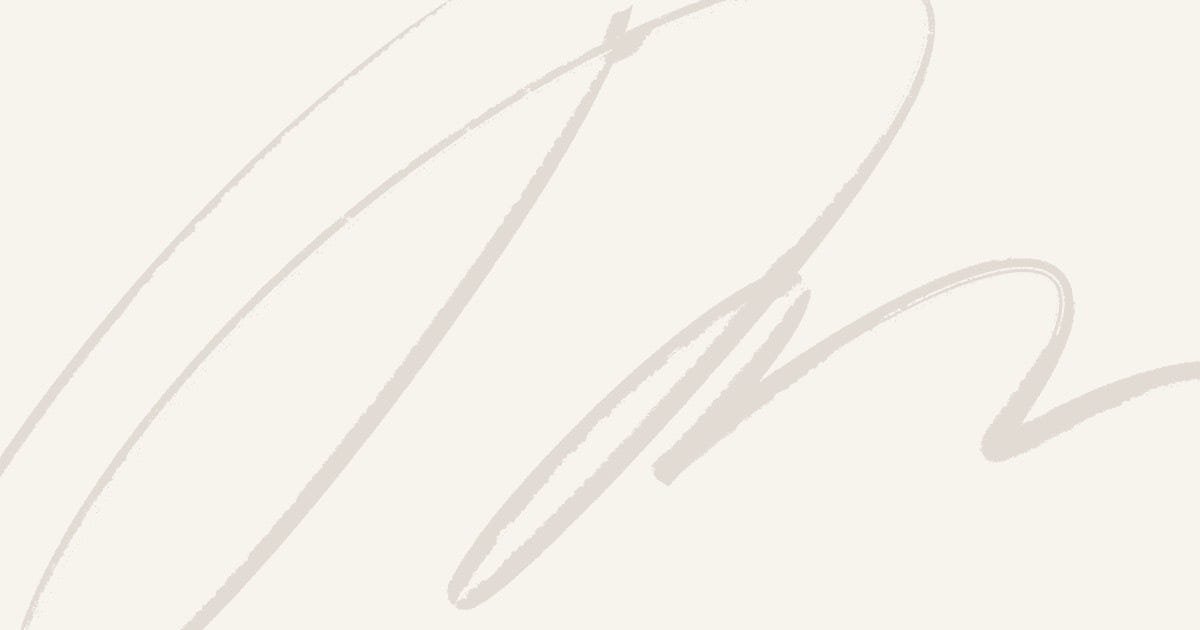Tiga Puluh Hari. Ada pertemuan yang ditakdirkan hanya… | by Aditya Wicaksono | Aug, 2025

“Tak ada yang lebih indah dari pertemuan yang sederhana, lalu diam-diam menjadi awal dari segalanya.”
Setiap kisah selalu memiliki pintu pertama untuk diketuk. Bagi saya, pintu itu terbuka pada sebuah hari yang sebenarnya biasa saja, namun ternyata menjadi hari paling bersejarah dalam hidup saya.
Teman saya di divisi Sumber Daya Manusia, suatu siang berkata, “Mas Adit, kandidat staf untuk sampean sudah ada ya. Dari IPB jurusan Agribisnis Pertanian kalau nggak salah, nanti besok jam 10 pagi interview user sama technical test langsung sama sampean ya mas.” Saya menanggapi dengan rasa heran, sedikit bercampur tawa, “Serius nih mas, dari jurusan Pertanian bakal bantu saya di translation and document?” Namun teman saya menjawab dengan mantap, “Iya mas, pasti cocok ini. Pintar kok anaknya.” Saya mengangguk, meski dalam hati masih belum percaya.
Hingga keesokan harinya, sosok itu datang. Pintu ruangan terbuka pelan, dan masuklah seorang perempuan muda dengan langkah sopan, raut wajah teduh, serta senyum yang seolah membawa ketenangan. Dengan balutan kemeja biru muda dan hijab berwarna putih, disertai tatapan matanya jernih, seakan ada kesejukan di dalamnya. Ia menyapa saya dengan suara lembut yang masih begitu jelas terngiang hingga kini. “Selamat pagi, Pak Aditya.” Panggilan “Pak Aditya” itu adalah kata pertama yang keluar dari bibirnya untuk saya. Sederhana, namun justru menjadi kata yang menandai awal segalanya.
Ia memperkenalkan diri dengan runtut. “Nama saya Ayunda Damai Pramesvari, bisa dipanggil Ayunda, pak. Sejak kecil saya lahir dan tinggal di daerah Sidotopo, Surabaya, dan ketika masuk SMP baru pindah ke Depok, lalu melanjutkan kuliah di IPB.” Perkenalan yang singkat, tapi cukup untuk memberi kesan pertama yang begitu kuat. Aksen Jawa Timurnya masih melekat jelas. Saat saya ajak berbincang santai dengan bahasa Jawa, ia membalas dengan bahasa Kromo Inggil yang halus dan penuh unggah-ungguh. Seketika saya tercengang — bukan hanya oleh kepandaiannya, tapi juga oleh rasa hormat dan kearifan yang ia tunjukkan lewat tutur kata. First impression itu menancap kuat, hingga kini tidak pernah saya lupakan.
Hari-hari setelahnya berjalan dengan alami. Yang tadinya hanya rekan kerja, perlahan berubah menjadi teman bicara, lalu menjadi teman berbagi banyak hal. Kami menghabiskan waktu berdiskusi, bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang buku, tentang hidup, tentang mimpi. Dan semakin lama saya mengenalnya, semakin saya menyadari betapa banyak kesamaan yang kami miliki.
Kami tinggal di lokasi yang tidak berjauhan, maka hampir setiap hari kami berangkat dan pulang bersama. Menyusuri sepanjang jalan Semanggi–Depok, merasakan macet yang biasanya membuat orang jengkel, tapi justru bagi kami menjadi waktu yang berharga. Obrolan di tengah kemacetan itu, tawa yang tiba-tiba muncul, atau bahkan diam yang terasa nyaman — semua menjadi benih kecil yang menumbuhkan kedekatan.
Sampai akhirnya, pada suatu sore dalam perjalanan pulang dari kantor, saya mengajaknya berbicara serius. Tidak ada restoran mewah, tidak ada hiasan bunga, tidak ada alunan musik romantis. Hanya ada kami berdua, duduk di dalam mobil, di tengah kemacetan Simpang Semanggi yang seolah menjadi saksi. Dengan suara bergetar tapi mantap, saya menyatakan kesungguhan hati saya padanya. Dan ia menjawab dengan sederhana pula — dengan sebuah senyum, lalu dengan panggilan baru yang mengubah segalanya. Sejak hari itu, ia berhenti menyebut saya “Pak”, dan menggantinya dengan “Mas”. Satu kata itu, “Mas”, begitu berarti. Sejak itulah hubungan kami dimulai.
“Cinta tidak selalu datang dengan gegap gempita. Kadang ia muncul pelan, sederhana, bahkan nyaris tanpa kita sadari. Namun justru dari kesederhanaan itu, ia tumbuh paling kuat.”
Kini, ketika saya menoleh ke belakang, saya bersyukur pada Tuhan atas pertemuan itu. Pertemuan yang sederhana, yang bahkan mungkin tidak akan saya perhitungkan sebelumnya. Namun dari ruang kerja yang biasa saja, dari obrolan singkat dengan aksen Jawa Timur yang khas, dari panggilan “Pak” yang kemudian berubah menjadi “Mas”, saya akhirnya menemukan belahan jiwa saya.
“Kita tidak pernah benar-benar tahu kapan cinta mulai bekerja. Tiba-tiba ia hadir, diam-diam bersemi, dan tumbuh menjadi bagian dari hidup yang tidak mungkin kita lepaskan.”
Awal mula itu, kini, menjadi kenangan yang saya genggam erat. Bahwa cinta terbesar dalam hidup saya lahir bukan dari sesuatu yang direncanakan dengan megah, melainkan dari sebuah pertemuan biasa, yang kemudian berubah menjadi luar biasa.