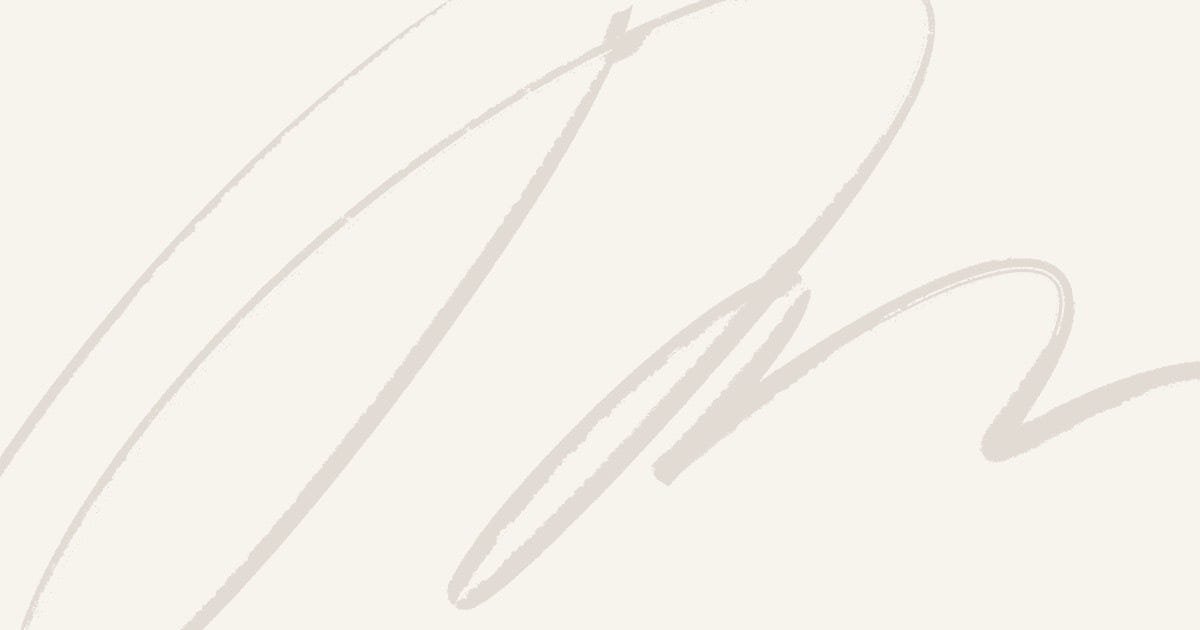Tentang Menjadi “Pelajar dari Dunia Ketiga” di Eropa | by ikananas | Oct, 2025

Mempelajari teori-teori dekolonial adalah keseharian yang kami jalani di Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada, dan sepertinya saya ingin mengatakan bahwa saya menempatkannya sebagai salah satu bagian yang paling personal dalam hidup saya. Di setiap mata kuliah, hampir pasti ada kata “coloniality” dan “decoloniality” yang saya tuliskan di buku catatan, dan ini terjadi di hampir setiap sesi. Mempelajarinya tentu bukan hal yang mudah. Saya masih bisa mengingat bagaimana hati ini patah setiap kali di kelas kami mendiskusikan apa yang diwariskan oleh kolonialisme — dan seluruh sistem yang mendukungnya — hingga hari ini di banyak tempat di dunia, salah satunya di komunitas-komunitas adat di Indonesia. Hal yang berulang kali kami tegaskan dan coba yakini bersama adalah: meskipun hari ini pendudukan langsung setidaknya berkurang dari apa yang terjadi sejak abad ke-16, sistem yang menopangnya tidak pernah benar-benar menghilang. Tidak ada yang berada “di luar” kolonialitas, sebab keseluruhan sistemnya ditopang oleh berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari.
Mempelajari ide-ide dekolonialitas berhari-hari kemudian membuat saya sedikit lengah, menganggapnya sebagai sesuatu yang selalu harus ada dalam pembahasan, hal yang disetujui semua orang, dan kita semua sedang bergerak di batas-batasnya untuk mencoba membuat retakan — meminjam istilah dari Catherine E. Walsh — pada dinding-dindingnya. Saya optimis, hingga tibalah saya di suatu sore yang gerimis di Salzburg, Austria. Saat itu, saya disambut oleh seorang yang sangat ramah di kantor urusan internasional sebuah universitas — sebut saja namanya Gina — dan dia mengatakan, “Oh yes, she is the one who takes care of students from Third World countries,” saat merujuk ke salah satu koleganya yang mengundang saya ke kantor itu. Gina mengatakannya dengan ceria, bahkan tanpa nada merendahkan, mungkin hanya sebuah kategori administrasi yang sepele. Namun, saya bisa merasakan ketidaknyamanan yang tidak biasa, yang belum pernah sekuat ini.
Kalimat itu menggantung begitu saja. Saya hanya mengangguk saat Gina, dengan gestur yang sangat terbuka, mengarahkan saya menuju meja kerja Alice, koleganya yang mengurusi pelajar dari negeri-negeri jauh seperti saya. Alice dan saya bertukar kabar. Hal pertama yang ia tanyakan tentu saja adalah, “Bagaimana perjalananmu?” Langsung kujawab, “Oh tentu saja melelahkan, saya menghabiskan 30 jam di perjalanan, tetapi kota ini sangat indah, dan sekarang saya baik-baik saja.” Ia kemudian membalas, “Ah, kami sangat senang kamu bisa datang hari ini, kami sangat mengerti bahwa perjalananmu pasti melelahkan.” Selebihnya, kami menyelesaikan urusan administrasi — surat-surat, stempel-stempel — dan selesai. Saya pulang membawa sebuah tote bag berwarna coklat muda dari bahan katun daur ulang, sebuah map berisi buku catatan, serta kartu pelajar. Setidaknya, seharusnya saya merasa senang. Saya resmi menjadi bagian dari salah satu tradisi akademik tertua di negeri ini, bahkan mungkin di dunia.
Mengenakan jaket semi-waterproof hitam bertuliskan CRCS untuk melindungi diri dari gerimis, saya berjalan pulang dengan kalimat “Third World Countries” yang terus menggema di kepala. Saya tersadar bagaimana saya baru saja didefinisikan dan ditempatkan dalam sebuah hierarki global. Pada saat itu saya menyadari bahwa saya bukan hanya seorang pelajar, tetapi perwakilan dari sebuah kategori geopolitik yang telah mapan. Saya teringat kembali betapa panjang dan rumitnya perjalanan yang harus saya tempuh untuk tiba di benua biru — urusan birokratik, ketentuan finansial, dan hal-hal lain yang seolah menuntut kami untuk terus-menerus membuktikan kelayakan. Sebuah kerumitan yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang dari Eropa yang ingin melancong ke “Timur”. Perasaan inferioritas bahasa juga menekan dan seolah meremukkan punggungku perlahan; saya menyadari besarnya tekanan untuk bisa sempurna dalam bahasa yang secara historis digunakan untuk menegaskan bahwa bahasa ibu saya tidak lebih berharga. Semua ini kemudian membawa saya pada sebuah pertanyaan: dapatkah saya benar-benar mengerjakan, menuliskan, dan bertindak dalam semangat dekolonialitas selagi saya berada di sini, di Barat? Apakah saya kemudian akan — atau bahkan telah — menjadi salah satu dari mereka?
Istilah “Dunia Ketiga” tentu bukanlah sesuatu yang netral. Ketidaknyamanan yang saya rasakan terasa tervalidasi saat saya membaca tulisan Walter Mignolo tentang the Colonial Matrix of Power, sebuah konsep yang ia kembangkan dari pemikiran Aníbal Quijano. Matriks ini adalah logika tersembunyi yang menopang modernitas, atau yang Mignolo sebut sebagai the darker side of modernity. Narasi-narasi tentang pembangunan, rasionalitas, dan kemajuan adalah logika yang tidak bisa dipisahkan dari kolonialisme, yang menciptakan tatanan dunia hierarkis dengan menempatkan manusia dan wilayah dalam sebuah peringkat: ada yang di atas dan yang lainnya di bawah, ada yang di pusat dan yang lainnya di pinggiran.
Perjalananku yang rumit ke Eropa, jika disandingkan dengan perjalanan mereka yang mudah, adalah konsekuensi langsung dari bekerjanya matriks ini — rezim visa, kesenjangan ekonomi, dan sistem pendidikan hierarkis yang mengatur arus pengetahuan global. Kalimat yang tampaknya sederhana dari Gina bukanlah cerminan karakter personalnya, melainkan sebuah refleksi dari struktur kekuasaan yang telah menubuh.
Selain itu, ketidaknyamanan yang saya rasakan adalah apa yang disebut oleh Sylvia Wynter sebagai the coloniality of being. Wynter mengatakan bahwa proyek kolonialisme menunjukkan “the overrepresentation of one particular version of human,” yaitu manusia Barat, borjuis, dan sekuler sebagai standar dan bentuk universal kemanusiaan. Dengan standar ini, diciptakanlah kelompok-kelompok orang yang dikondisikan untuk harus mengejar standar tersebut — the Human Other — yang dianggap irasional dan primitif. Maka ketika Gina dan Alice, melalui sistem pendidikan tinggi di Eropa, melabeli saya sebagai students from third world countries, sistem ini memposisikan saya sebagai Human Other yang perlu mengejar standar universal “Manusia” tersebut.
Jadi, apakah berada di Salzburg kemudian membuat saya tidak lagi pantas untuk berada dalam proyek dekolonial? Atau membuat suara saya tidak berarti sebab saya menikmati menjadi bagian dari sistem pendidikan tinggi Eropa? Pemikiran Mignolo tentang reside dan dwell kemudian membantu saya menemukan jawabannya. Residing in the West adalah sebuah fakta fisik, tetapi saya tidak perlu dwell di sini dengan menerima logika imperialnya. Luka-luka kolonial yang saya bawa melalui tubuh, pemikiran, dan memori adalah hal yang sesungguhnya menciptakan ketidaknyamanan yang kuat tadi. Tubuh saya mencegah saya untuk berasimilasi dengan kenyamanan berada di tanah tempat konsep-konsep rasionalitas dan kemajuan ini berasal.
Namun, saya juga masih terus bertanya-tanya. Dengan keistimewaan yang saya rasakan hari ini di Eropa — menikmati aliran sungainya, udara yang lebih bersih, air keran yang bisa diminum, bangunan-bangunan megah yang telah berdiri sejak 600–800 tahun lalu, yang beberapa bulan lalu hanya bisa saya saksikan di buku-buku sejarah — apakah semua yang saya alami ini dapat membantu saya melakukan pembangkangan epistemik yang dibicarakan Mignolo? Ataukah ini adalah bentuk asimilasi paling halus, di mana urgensi untuk mempertanyakan semua hal perlahan-lahan ditukar dengan kenyamanan yang saya nikmati setiap hari?