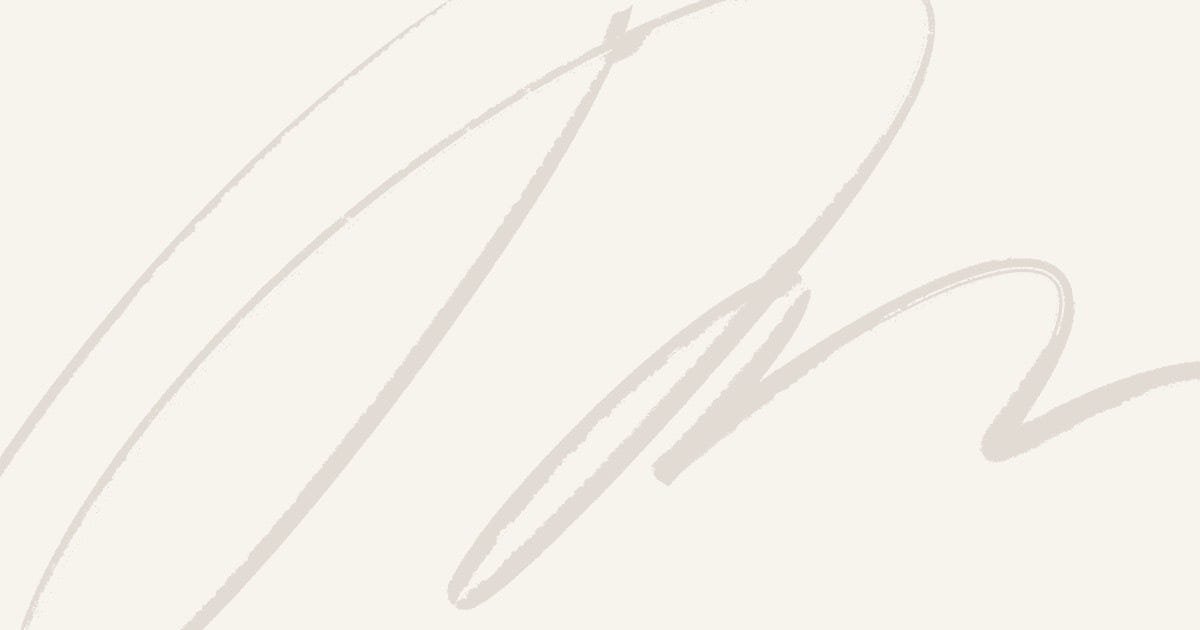Tempat Pembuangan. Semua Orang Punya Cerita. Tapi Kenapa… | by Zi | Jul, 2025

Sudah hari keempat aku di Balikpapan. Aku bilang ke mama ini urusan kerja, padahal kantor cuma butuh bantuanku untuk audit kecil dua minggu. Kupikir aku akan bosan. Tapi kota ini menyambutku dengan hal-hal aneh: warung kopi yang menaruh bunga kamboja di dekat asbak, dan suara azan yang terdengar lebih jujur dibanding suara notifikasi HP-ku.
Kos-kosan yang kutempati tidak seperti biasanya. Terlalu rapi. Terlalu terang. Bantalnya terlalu wangi. Ada AC, ada kolam renang kecil yang airnya diam. Di sinilah aku bertemu Rani. Perempuan yang awalnya kutebak sebagai karyawan bank atau mungkin pegawai skincare online karena kulitnya bersih, senyumnya rapi, dan langkahnya terdengar seperti punya arah.
Ternyata dia hanya… ibu. Ibu dari tiga anak. Janda.
“Aku baru pindah ke sini bulan lalu,” katanya waktu kami pertama kali bertemu di dapur bersama. Ia sedang memeras jeruk untuk anaknya yang batuk. “Kos-kosan bougie begini mahal, tapi demi anak-anak, ya sudahlah. Mereka bilang aku egois kalau tinggal di tempat jelek.”
Aku hanya mengangguk, menyalakan kompor, merebus air. Tanganku gemetar sedikit saat menabur kopi bubuk ke dalam cangkir. Rani duduk di meja makan kecil, napasnya panjang, tatapannya kosong. Bukan lelah. Tapi luka yang sudah jadi hantu.
“Orang-orang pikir aku minta dikasihani,” lanjutnya. “Padahal aku cuma minta jangan ditatap seolah aku najis.”
Aku terdiam. Asap rokokku mengepul ke arah jendela dapur yang terbuka. Angin sore membawa aroma cucian basah, campur sedikit bau bawang goreng dan solar. Di luar, suara anak-anaknya tertawa. Aku sempat berpikir, suara mereka terlalu ringan untuk kos ini.
“Waktu itu, anak keduaku nangis di kelas. Gara-gara temannya bilang aku janda yang suka gonta-ganti laki-laki.”
Kali ini aku menoleh. “Kamu lapor?”
“Lapor ke siapa?” katanya lirih, lalu tertawa. “Ibunya temannya itu… kakak sepupuku.”
Kami diam sebentar. Lalu dia tertawa lagi, bukan karena lucu, tapi seperti ingin muntah. Aku ikut tertawa. Entah kenapa, semua cerita paling menyedihkan selalu terdengar seperti komedi jika dikisahkan oleh seseorang yang sudah putus harapan.
“Aku kerja apa saja sekarang. Asal halal, kata ibuku. Jualan online, sesekali bantu-bantu dekor nikahan. Tapi tetap aja, orang cuma lihat: ‘Rani si janda.’ Udah kayak embel-embel merek.”
Aku ingin bertanya, mana suaminya. Tapi rasanya pertanyaan itu akan membuka ruang yang tidak berhak aku sentuh. Jadi aku hanya menawarkan rokok. Ia menolak. “Aku sudah berhenti. Anak-anakku benci asap,” katanya. Dalam hati aku merasa bersalah. Tapi aku tetap mengisap batangku sampai ujungnya mati sendiri di jari.
Kami mulai sering duduk di dapur malam-malam. Kadang ia bercerita soal anak-anaknya yang suka rebutan remote, kadang soal keluarga yang hanya datang saat hari raya dan pergi setelah menghakimi. Kadang ia cerita soal laki-laki yang mencoba mendekatinya, hanya untuk tidur dengannya, lalu hilang seperti debu di pagi hari.
“Aku nggak butuh suami,” katanya suatu malam. “Aku butuh diam. Damai. Tapi dunia nggak percaya janda bisa bahagia sendirian.”
Malam itu hujan. Air merembes dari jendela dapur dan menetes ke lantai, membuat kaki kami basah. Tapi tak ada yang bergerak. Kami hanya duduk, mendengar detak waktu yang terasa lambat sekali.
Aku ingin cerita juga. Tentang pekerjaan baruku ini di perusahaan wine. Tentang rasa sepi yang tidak pernah selesai. Tentang hubungan yang harus kusimpan rapi-rapi dalam kepala, karena dunia masih belum siap.
Tapi aku tak bisa. Bibirku berat. Sementara Rani terus bercerita, seperti orang yang tidak pernah diajak bicara tanpa dihakimi.
“Aku pernah bilang ke anakku yang paling kecil,” katanya, “kalau aku mati, jangan nangis. Mama mati bukan karena sakit, tapi karena dunia membunuh mama sedikit-sedikit.”
Aku tercekat. Ingin menegur, ingin menyemangati, tapi kutahu kalimat itu bukan permintaan tolong. Itu cuma fakta.
Dua minggu hampir habis. Aku mulai membereskan koperku, mencuci baju-baju yang kubawa, mematikan lampu-lampu yang tidak perlu. Rani mengantarku sampai gerbang. Ia tidak menangis, tapi anak bungsunya melambai-lambaikan tangan kecil sambil memegang susu kotak.
“Kalau ke Balikpapan lagi, kasih kabar ya,” katanya.
Aku mengangguk.
Di perjalanan pulang, aku sempat berpikir: kenapa aku? Kenapa aku yang pendiam ini selalu jadi tempat orang-orang asing menggantungkan cerita hidup mereka? Dari Langit si perempuan sunyi di coffee shop dekat stasiun, sampai Rani si ibu yang dunia tak henti-henti mencacinya.
Dan aku sendiri, kepada siapa harus bercerita tentang dosaku?
Tentang hal-hal yang tak bisa kumengerti. Tentang malam-malam yang penuh pengakuan. Tentang perasaan yang tidak bisa kutebus dengan kata-kata.
Aku menyalakan rokok di halte bus sebelum berangkat pulang. Langit samar-samar merah. Samarinda masih seperti dulu. Tapi aku, mungkin sudah sedikit berubah.