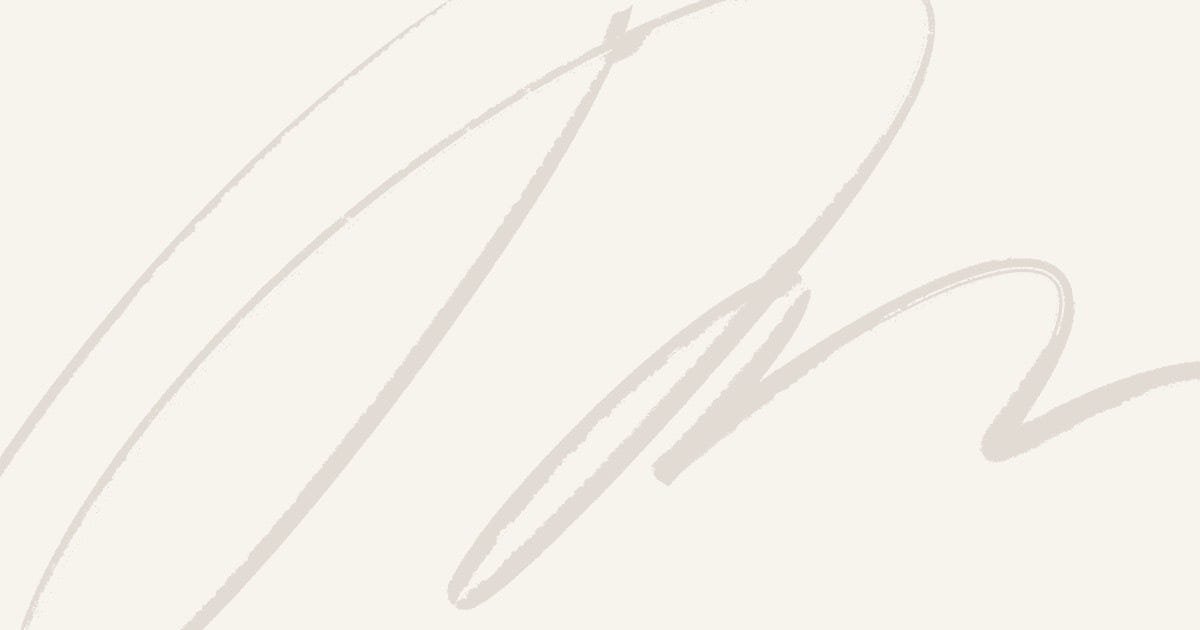Psikologi Islam, Editor, dan WFH. #2 Pengalaman menjadi seorang editor… | by Fira Yultiara | Oct, 2025
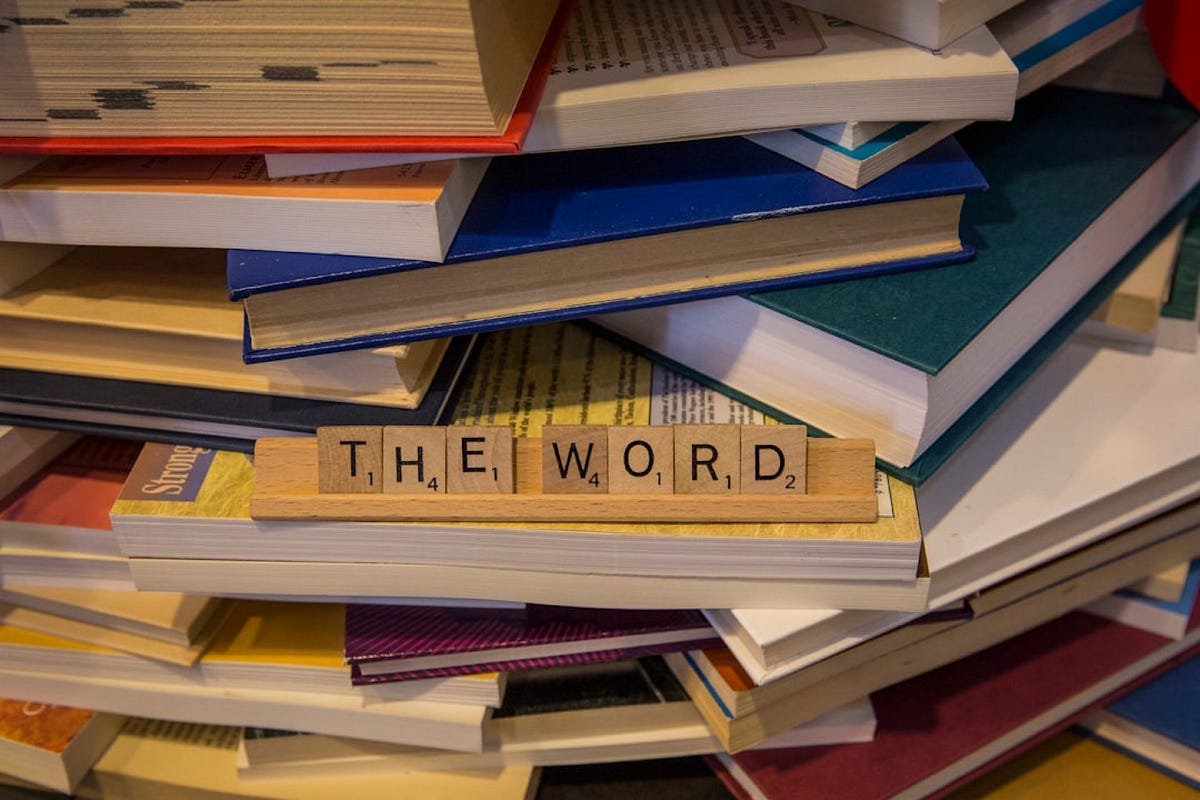
Tepat satu bulan setelah tugas sekaligus kontrak kerjaku sebagai editor di IOU berakhir. Untuk menggantikan tenggat waktu bulanan yang biasanya membayangi hari, aku mencoba menulis untuk menutup kisah mengenai pekerjaan pertama yang berharga.
Sampai saat ini, tidak terasa bahwa kata demi kata dalam setiap teks ilmiah yang perlu disunting, detik demi detik ucapan dosen yang perlu diterjemahkan sebagai sebuah takarir, dan lembar demi lembar catatan presentasi yang perlu diperindah agar nyaman dibaca itu akhirnya bisa terselesaikan. Meskipun mungkin masih jauh dari kata sempurna, aku harap tidak lagi sukar untuk dipahami.
Singkat cerita, hampir dua tahun lalu, aku diberi kesempatan untuk bekerja sebagai editor mata kuliah di kampus Bahasa International Open University (IOU), sebuah kampus terbuka dengan basis Islam dalam pendidikannya. Sebuah pekerjaan yang cukup unik, menurutku, karena aku tidak pernah membayangkan akan menjadi editor untuk studi Psikologi Islam, pekerjaan yang secara tidak langsung akan menjadi perpanjangan tangan bagi mahasiswa/i selama perjalanannya menuju seorang sarjana. Aku tidak menyangka bisa menggunakan ilmu yang kupelajari dengan cara ini, secepat ini, dengan kultur kerja yang begitu Islami. Jika tidak bekerja di sini, aku juga tidak akan sadar bahwa aku terlalu terbiasa memisahkan aspek agama dalam percakapan sehari-hari.
Rasanya menyenangkan bisa terlibat sampai akhir dalam proyek yang nantinya akan memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk menjadi sarjana Psikologi, memahami ilmu Psikologi secara lebih mendalam, dan memandang setiap manusia secara lebih empatik dengan basis Islam yang melekat di setiap mata kuliahnya. Di sisi lain, rasanya menyedihkan karena harus mengakhiri pekerjaan yang memberiku kesempatan untuk bekerja sekaligus belajar, juga lingkungan kerja yang dapat menyeimbangkan antara tuntutan dan pemahaman terhadap kapasitas pegawainya.
PSIKOLOGI DAN ISLAM
Psikologi yang terintegrasi dengan Islam merupakan ranah yang berulang kali menarik perhatianku, tetapi belum pernah kutemui dan benar-benar kusentuh sama sekali selama menempuh perkuliahan Psikologi di universitas. Hematku, agama dan manusia adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Bagi para pemeluknya, agama adalah identitas yang menjadi dasar dari setiap perbuatannya, dan cara pandangnya terhadap dunia. Bagaimana bisa sebuah intervensi akan menjadi menyeluruh ketika kita berusaha memisahkan separuh bagian yang membentuk jati diri orang tersebut saat berusaha memahami hingga membantunya sembuh? Sudah menjadi hal yang wajar jika kita mengintegrasikan keduanya.
Pekerjaan ini membuatku merasa seperti sedang menempuh sarjana Psikologi untuk yang kedua kalinya. Jika ditanya apakah berkesan? Tentu saja, belajar sekaligus mendapat bayaran itu sangat menyenangkan. Kali ini, alih-alih belajar Psikologi sembari memandang bahwa sekulerisme dan Barat sebagai pakem yang harus diikuti, aku mempelajari Psikologi dari sudut pandang dunia Islam, membuat diriku sendiri familiar dengan tokoh-tokoh Islam serta kitab suci dan hadits, yang ternyata begitu terpisah dari setiap ilmu yang kupelajari selama menempuh perkuliahan.
Ada satu hal yang memantik kesadaranku saat menghabiskan setengah perjalananku sebagai penerjemah dan subtitler. Saat ini, ada kebutuhan yang besar akan kehadiran psikolog Islam, atau setidaknya yang mampu mengintegrasikan keilmuannya dengan Islam. Tidak seperti masyarakat di negara mayoritas Islam seperti Indonesia, masyarakat di negara minoritas kesulitan untuk mendapatkan bantuan psikologis yang dilakukan tanpa perlu takut bahwa mereka akan tercerabut dari agamanya, belum lagi masalah diskriminasi yang harus mereka hadapi.
Jika aku bisa menyarankan pada orang lain mengenai mata kuliah dalam Psikologi Islam apa yang paling menarik, maka aku akan menjawab biological bases of behavior, alias neurosains. Mengintegrasikan neurosains dan Islam masih terasa ‘wah’ dalam pandanganku. Sebelum memikat mahasiswa/i, mata kuliah ini sudah terlebih dahulu memikat perhatianku saat bertanggung jawab untuk menyuntingnya. Waktu yang kuhabiskan untuk menyunting modul-modul yang berhubungan dengan neurosains, sekaligus menghabiskan puluhan jam untuk mendengarkan dosen yang merupakan seorang neuroscientist di Eropa, membuat rasa penasaranku terhadap bidang ini justru tumbuh sedikit demi sedikit.
MENJADI EDITOR SEKALIGUS SUBTITLER
Sebagai seorang mahasiswi semester akhir yang telah ditinggal lulus oleh sebagian besar temannya, pertanyaan yang paling sering muncul dalam percapakan di tengah masa-masa penuh krisis tersebut tentu saja, “Jadi, mau kerja apa setelah lulus?” Dengan asumsi bahwa semua pekerjaan yang bagus sudah diambil oleh mereka yang lulus terlebih dahulu. Dan aku, tanpa pengalaman nyata di bidang ini, disaat seharusnya aku menjawab ingin menjadi psikolog atau pekerjaan yang linear, acap kali aku malah menjawab, “Editor sih, kalau nggak editor ya penulis. Hidupku ga jauh-jauh dari itu.” Iya, mau bagaimanapun, pepatah mengenai ucapan adalah do’a bukan sekedar isapan jempol belaka. Sayang sekali aku tidak menjawab secara lebih spesifik di masa-masa itu. Contohnya, “Mau jadi pengangguran yang bisa keliling dunia tanpa mikirin duit.”
Cukup meresahkan, pada awalnya, membayangkan bahwa setiap kecacatan dalam penyuntingan dan penerjemahan yang mungkin akan kulakukan akan berdampak langsung pada mahasiswa/i yang nantinya akan menjadi seorang sarjana. Berhadapan dengan ayat Al-Qur’an dan hadits juga membuatku benar-benar harus menajamkan mata setiap kali bekerja, memastikan semuanya akurat, mulai dari konten hingga tata bahasa, karena masalahnya jauh lebih pelik jika ada kesalahan dalam penyuntingan dan penerjemahan.
Dalam bayanganku yang agak paranoid, aku bahkan sering berpikir, “Jika mereka gagal, maka aku turut andil dalam kegagalan mereka.” Namun, jika tempatku bekerja saja sudah memberikan kepercayaannya padaku, lantas apa yang membuatku tidak percaya pada diriku sendiri? Berangkat dari kesadaran itu, aku berusaha memberikan yang terbaik, sejauh yang dapat kulakukan.
Setelah mencicipi pekerjaan sebagai editor dan subtitler selama dua tahun, aku sadar bahwa masih banyaaaaak sekali hal yang harus kupelajari, baik itu dari segi editorial dan menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Pekerjaan ini juga membuatku tidak bisa lagi memandang buku-buku pelajaran, soal-soal, dan setiap takarir yang muncul di bawah video edukasi dengan cara yang sama. Perjalanan yang dipenuhi dengan mata yang kering dan minus yang bertambah akibat menatap laptop terlalu lama, kepala yang berdenyut setiap kali harus menerjemahkan penjelasan dosen yang bahasa ibunya bukanlah bahasa Inggris, dan beberapa kesalahan komunikasi serta penyesuaian yang harus dilakukan di antara tim editor.
BEKERJA DARI RUMAH
“Oh … Jadi ini yang disebut pekerjaan idaman? Bekerja sembari menatap dinding kamar yang putih bersih selama tujuh jam penuh?” gumamku–setengah bercanda–pada diriku sendiri karena sedang bekerja dari rumah bertemankan laptop, sembari teringat sebuah istilah dalam dunia Psikologi yang disebut dengan white torture [re: siksaan ruang putih].
Bekerja dari rumah (WFH/Work From Home) tentunya punya tantangannya tersendiri. Sebelum bekerja, aku kesal jika harus berkoordinasi secara daring, dan lebih menyukai interaksi secara langsung. Ketikan dalam pesan singkat juga bisa diinterpretasikan secara berbeda-beda, menimbulkan kesalahpahaman yang tidak penting. Saat masih berkuliah, aku bahkan lebih memilih menunggu pandemi Covid-19 itu mereda agar bisa mendatangi dosen secara langsung saat meminta bimbingan skripsi. Namun, manusia memang tidak boleh dan tidak bisa terus hidup dalam kenyamanannya. Hal-hal yang dulu sangat aku hindari justru menjadi bagian dari hidupku. Nyatanya tidak seburuk itu, hanya perlu sedikit pembiasaan.
Setelah dijalani cukup lama, aku mulai menyadari apa yang diidam-idamkan sebagian besar orang ternyata masuk akal. Meskipun aku tetap harus menghabiskan waktu yang panjang di balik laptop dengan fokus yang maksimal, aku tidak terlalu terikat oleh jam kerja, tidak perlu pusing memikirkan pakaian apa yang perlu dikenakan, dan bisa bepergian dengan santai atau sekedar bergabung dengan berbagai komunitas di siang hari karena jam kerja yang fleksibel. Semua itu adalah sebentuk kebebasan yang nyatanya begitu berharga.
Lagipula, menyenangkan atau tidaknya sebuah pekerjaan sangat bergantung pada seseorang yang menjalaninya. Pekerjaan yang mencekik sekalipun akan tetap memiliki posisi yang menyenangkan bagi orang-orang tertentu, yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya, karena keterbatasan dalam kapasitas pengandaian kita. Sekarang, masa-masa sebagai editor di IOU itu sudah berakhir dengan memuaskan, dan aku penasaran dengan pengalaman apa yang akan kuhadapi dari perjalananku selanjutnya.