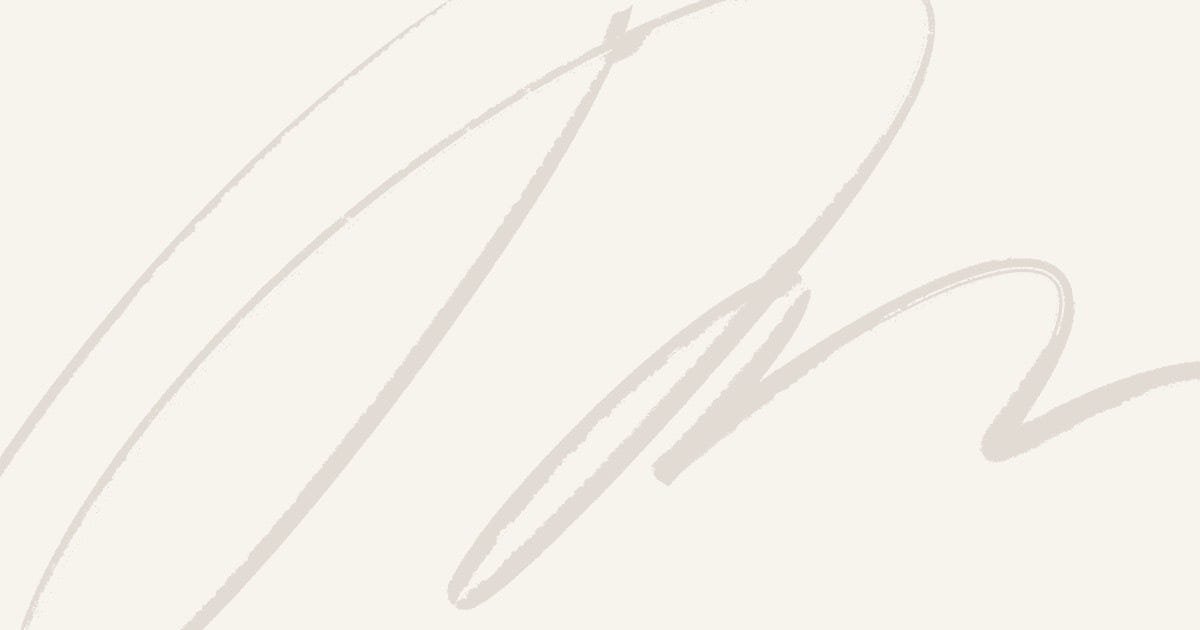Kenangan Pahit di Usia 4 Tahun: Saat Bapak Pergi dan Tak Pernah Kembali | by A Rahmat Faisal | Aug, 2025

Tahun 1998 seharusnya menjadi masa di mana saya, Rahmat Faisal, menikmati hari-hari penuh tawa dan kasih sayang dari kedua orang tua. Namun, hidup kadang tak berjalan sesuai harapan. Di usia 4 tahun, saya harus menghadapi kenyataan pahit: perceraian orang tua.
Kenangan itu masih begitu jelas dalam ingatan saya, seperti film lama yang terus diputar ulang setiap kali saya mengingat masa kecil. Bukan kenangan yang ingin saya simpan, tapi ia tetap tinggal, mengendap di sudut hati dan pikiran.
Hari itu, suasana di rumah terasa tegang. Ada keributan antara Bapak dan Mama. Saya yang masih kecil hanya bisa melihat dari sudut ruangan, tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Suara mereka meninggi, nada bicara penuh emosi, dan mata keduanya tampak memendam luka.
Tiba-tiba, Bapak keluar dari rumah. Ia masih mengenakan seragam kerjanya — warna dan baunya masih begitu saya ingat. Bapak berjalan menuju belakang rumah, melewati lapangan bola yang menjadi jalur pintas.
Naluri seorang anak membuat saya tak bisa diam. Saya berlari mengejarnya, kaki kecil saya menapaki tanah berdebu, berusaha mendekat.
“Bapak mau pergi ke mana?”
tanya saya dengan napas terengah.
Bapak menoleh. Sorot matanya berbeda — mata itu berkaca-kaca, seperti menahan sesuatu yang berat. Ia menjawab singkat,
“Mau pergi…”
Tidak banyak kata yang keluar dari bibirnya. Diam, hening, dan langkahnya terus menjauh. Seolah setiap langkahnya menghapus jarak antara kami, tapi memperlebar jurang yang akan memisahkan kami selamanya.
Sebagai anak berusia 4 tahun, saya belum mengerti arti perceraian. Yang saya tahu hanya satu: Bapak pergi dan tidak kembali lagi. Rumah kecil yang dulu terasa hangat kini menjadi sepi. Ada kursi kosong di ruang tamu, ada gelas kopi yang tak lagi diisi setiap pagi, dan ada suara tawa yang hilang dari meja makan.
Bapak meninggalkan lebih dari sekadar rumah. Ia meninggalkan bagian dari diri saya — rasa aman, pelukan hangat, dan perhatian yang hanya seorang ayah bisa berikan. Dan meski saya masih kecil, kehilangan itu sudah terasa begitu nyata.
Tak lama setelah itu, Mama mengambil keputusan yang juga mengubah hidup saya. Ia memutuskan bekerja di Cakung, Jakarta Timur, dan kos di sana. Pekerjaan itu membuatnya hanya bisa pulang setiap akhir pekan — Sabtu siang hingga Minggu malam.
Artinya, kebersamaan saya dengan Mama hanya 2 hari 1 malam setiap minggu. Sisanya, saya tinggal di rumah bersama Engkong Rasim, Nenek Kosih, dan Mamang Muhammad Soleh.
Saya tahu Mama bekerja keras demi masa depan saya. Tapi di usia sekecil itu, yang saya butuhkan bukan hanya uang atau pakaian baru — yang saya butuhkan adalah kehadiran.
Bayangkan seorang anak berusia 4 tahun yang harus melewati hari-harinya tanpa kedua orang tua. Pagi hari tanpa pelukan Mama, malam hari tanpa ucapan selamat tidur dari Bapak. Saya sering merasa iri melihat teman-teman sebaya yang diantar ayahnya ke sekolah atau dijemput ibunya saat bermain.
Engkong dan Nenek memberikan cinta mereka dengan tulus, tapi tetap saja ada ruang kosong di hati yang tak bisa diisi siapa pun. Itu adalah ruang untuk Bapak dan Mama — ruang yang kini hanya bisa diisi oleh kenangan.
Sesekali, Bapak datang menengok saya. Tapi kunjungan itu jarang, dan selalu terasa terlalu singkat. Ia datang, menanyakan kabar, tersenyum tipis, lalu pergi lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk bermain bersama atau bercerita panjang. Hubungan kami perlahan menjadi seperti tamu dan tuan rumah, bukan lagi ayah dan anak.
Saya tak pernah tahu pasti apa yang Bapak rasakan saat itu. Mungkin ada rasa bersalah, mungkin ada luka yang ia bawa sendiri. Tapi yang pasti, ia tetap Bapak saya, dan saya tetap merindukannya.
Masa-masa itu adalah salah satu periode paling sulit dalam hidup saya. Saya masih terlalu kecil untuk mengerti konflik orang dewasa, tapi cukup besar untuk merasakan kehancuran dunia kecil saya.
Saya pernah mencoba melupakan, tapi ada momen-momen tertentu yang memicu ingatan itu kembali — seperti saat melihat anak kecil digandeng ayahnya, atau mendengar suara orang tua bertengkar. Rasa sesak itu selalu muncul, seolah saya kembali menjadi anak 4 tahun yang berlari mengejar Bapaknya.
Meskipun pahit, masa itu mengajarkan saya banyak hal:
- Kehadiran lebih berharga dari apapun
Anak-anak tak butuh banyak harta, mereka butuh orang tua yang hadir di sampingnya. - Cinta kadang kalah oleh keadaan
Saya percaya Bapak dan Mama mencintai saya, tapi keadaan membuat mereka harus berpisah. - Kekuatan datang dari luka
Hidup tanpa kedua orang tua di usia kecil membuat saya tumbuh lebih mandiri dan kuat. - Menghargai setiap momen bersama
Karena saya tahu betapa berharganya waktu ketika bersama orang yang kita cintai.
Kini, setelah dewasa, saya menyadari bahwa luka masa kecil itu membentuk saya. Saya belajar berdiri di atas kaki sendiri lebih cepat dari anak-anak lain. Saya belajar mengandalkan diri sendiri ketika butuh sesuatu. Dan yang terpenting, saya belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama pada generasi berikutnya.
Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa memilih bagaimana masa depan saya. Saya ingin menjadi seseorang yang hadir penuh untuk orang-orang yang saya cintai. Karena saya tahu rasanya kehilangan itu seperti apa.
Tahun 1998 akan selalu menjadi bagian penting dari kisah hidup saya. Bukan karena saya ingin mengingatnya, tapi karena ia mengajarkan saya pelajaran yang tak bisa diajarkan oleh buku atau sekolah.
Perceraian orang tua memang meninggalkan luka, tapi dari luka itu saya menemukan arti cinta, kehadiran, dan keteguhan hati. Dan meskipun saya hanya punya sedikit momen bersama Bapak di masa kecil, momen itu tetap akan saya simpan seperti harta karun yang tak ternilai.
kisah hidup Rahmat Faisal, perceraian orang tua, pengalaman masa kecil, cerita keluarga Indonesia, kehilangan orang tua, kisah inspiratif anak, masa kecil di Bekasi, kenangan bersama ayah.
#RahmatFaisal #KisahHidup #Bekasi #PerceraianOrangTua #CeritaKeluarga #KenanganMasaKecil #InspirasiHidup #Kehilangan #MotivasiHidup