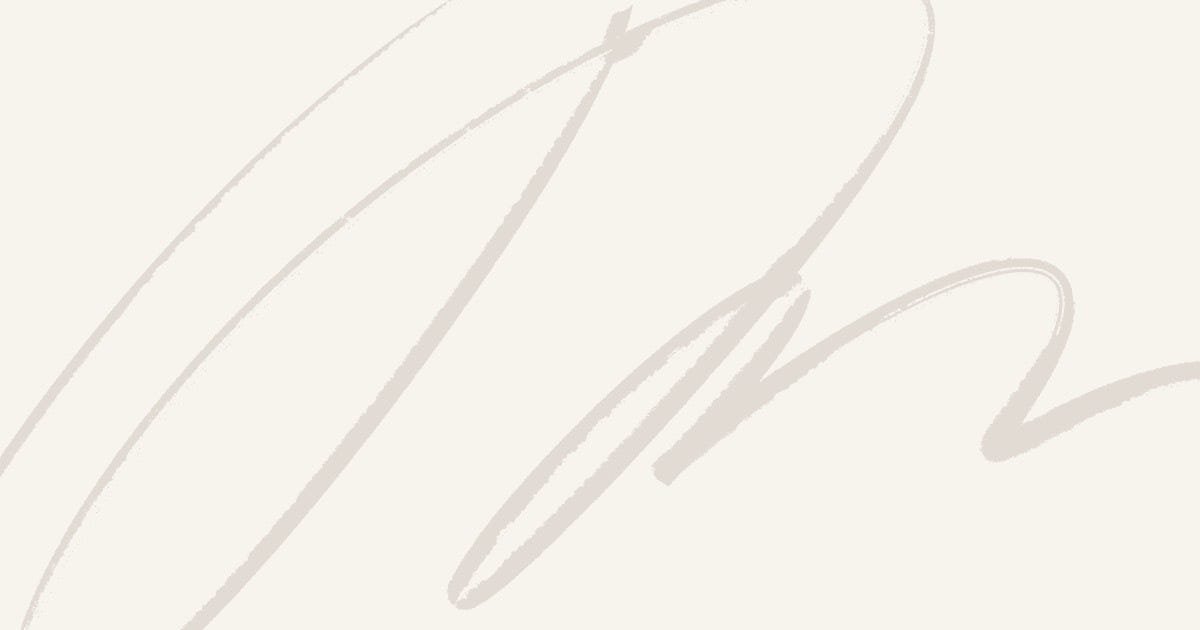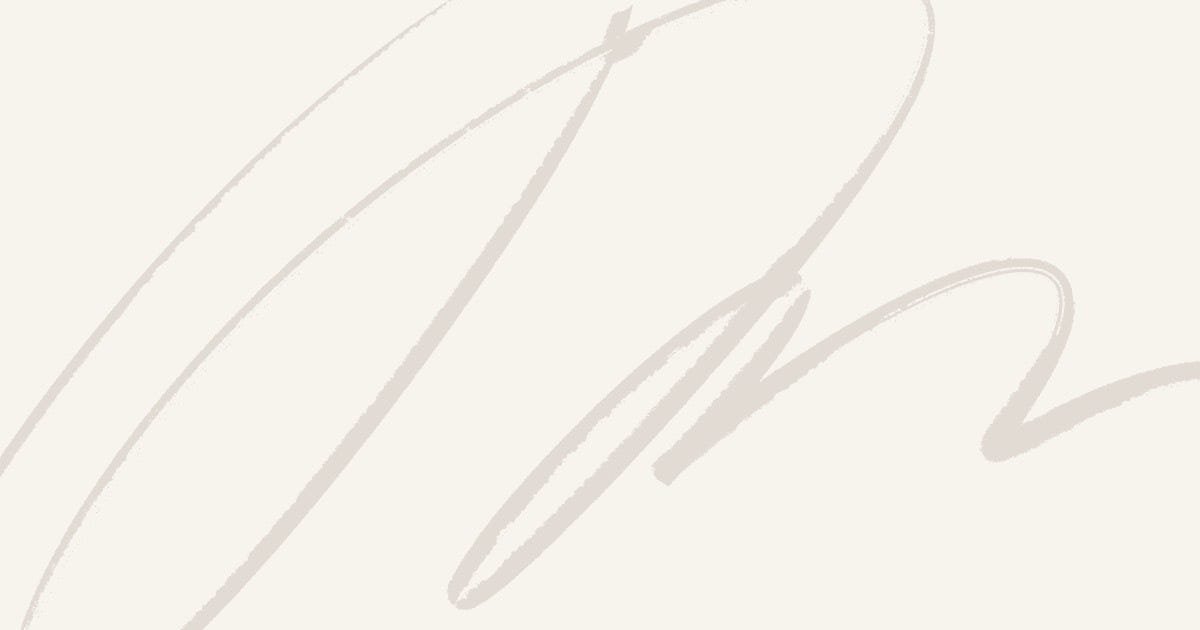Kayla. Salon di Gang Jalan Cendana | by Zi | Jul, 2025

Aku tidak berencana masuk ke salon kecil di ujung gang di Jalan Cendana. Tapi hujan turun tiba-tiba—bukan hujan romantis seperti di film, melainkan hujan tropis Samarinda yang mengubah jalanan jadi lautan berlumpur dan memaksa siapa saja mencari perlindungan terdekat.
Salon “Kemiri” bukan tempat yang mewah. Cat dindingnya sudah mengelupas di beberapa sudut, cermin-cermin kecil dipasang tidak sejajar, dan aromanya campuran antara hair spray murah dan pewangi ruangan beraroma bunga mawar palsu. Di pojok, televisi kecil memutar sinetron siang dengan volume yang terlalu keras.
“Masuk aja, Kak. Tunggu hujannya reda,” kata perempuan berusia sekitar tiga puluhan yang sedang mencuci rambut pelanggan di wastafel. Suaranya ramah, tapi ada kelelahan yang tertangkap di intonasinya.
Aku duduk di kursi plastik yang tersedia. Salon ini sederhana—dua kursi potong rambut, satu wastafel, dan satu meja kecil berisi peralatan tata rambut yang sudah tidak begitu terawat. Tapi ada kehangatan di sini. Kehangatan yang tidak dibuat-buat.
Perempuan tadi memperkenalkan diri sebagai Kayla sambil mengeringkan tangannya dengan handuk kecil yang sudah pudar warnanya. Rambutnya diikat tinggi, beberapa helai lepas menempel di keningnya yang berkeringat. Wajahnya lelah, tapi matanya masih menyimpan kebaikan.
“Pulang kerja kah, Kak?” tanyanya sambil membereskan botol-botol shampo.
“Lagi jalan-jalan aja,” jawabku. Aku memang sedang keluar rumah setelah seharian bekerja dari rumah, dan hujan ini tiba-tiba turun saat aku sedang mencari udara segar.
Kayla mengangguk. “Oh warga sini juga? Gang ini memang agak terpencil.”
Pelanggannya—seorang ibu paruh baya—selesai dan pergi setelah membayar lima belas ribu untuk cuci blow. Kayla merapikan kembali tempat duduknya dan mulai menyapu potongan rambut di lantai.
Aku mengangguk saja.
“Buka salon sendiri sudah lama?”
“Iya. Udah hampir dua tahun.” Kayla berhenti menyapu sejenak. “Bukan karena hobby sih. Lebih karena… terpaksa.”
Ada jeda dalam kalimatnya. Jeda yang familiar bagiku—jeda yang biasanya muncul sebelum cerita yang tidak mudah diceritakan.
Hujan masih deras. Aku tidak buru-buru pergi.
Kayla meletakkan sapunya dan duduk di kursi seberang. Kayla meletakkan sapunya dan duduk di kursi seberang. “Dulu aku guru TK. Di TK Swasta, dekat rumah. Enam tahun kerja di sana.”
Wajahnya berubah. Senyum yang tadi sempat muncul perlahan memudar. Tangannya mulai memainkan gelang plastik di pergelangan tangannya—gerakan nervous yang tidak disadari.
“Kenapa berhenti? Karena video,” katanya pelan, seolah sudah tahu aku akan bertanya.
Aku tidak bertanya lebih lanjut. Sudah cukup sering aku mendengar kalimat yang dimulai seperti itu. Dan aku tahu, biasanya mereka akan bercerita sendiri jika diberi ruang dan waktu.
Kayla menatap lantai salon yang sudah bersih. “Susah percaya sama siapa-siapa jaman sekarang.”
Dia berdiri, mengambil gelas dan menawarkan air putih. Aku terima.
“Aku punya pacar. Namanya Doni. Pacaran hampir tiga tahun. Aku pikir dia serius, soalnya dia sering ngomong soal nikah, ngomong soal masa depan. Bahkan udah dikenalkan ke keluargaku.”
Kayla duduk lagi. “Pas kita pacaran, dia sering minta… ya namanya juga cinta. Kadang dia bilang ‘buat kenang-kenangan’ katanya. Aku bodoh, aku kasi. Aku percaya sama dia.”
Suaranya mulai bergetar. Tapi tidak ada tangis. Hanya kelelahan.
“Pas kami putus—karena dia selingkuh sama temen kantor—dia ngancam aku. Bilang kalau aku berani cerita ke orang atau ganggu hubungannya sama cewe baru, dia bakal sebarin video-video itu.”
Kayla menggenggam gelasnya erat. “Aku nggak cerita ke siapa-siapa. Aku cuma diam. Tapi entah kenapa, beberapa bulan kemudian kepala sekolah manggil aku. Katanya ada yang lapor, ada yang kirim video ke grup chat orangtua murid.”
Matanya kosong. “Dalam semalam, semua berubah. Orangtua murid protes. Ada yang bilang aku nggak pantas ngajar anak-anak. Ada yang bilang aku merusak citra sekolah. Kepala sekolahnya sendiri bingung. Aku guru yang baik, katanya. Tapi ini masalah image.”
“Terus diminta resign?”
“Iya. Bukan dipecat secara resmi, tapi diminta berhenti dengan baik-baik. Biar nggak ribet katanya.”
Kayla tertawa pahit. “Lucu ya. Aku yang jadi korban, tapi aku yang harus minggir. Doni? Dia biasa aja. Bahkan masih bisa jalan-jalan ke mall sama pacar barunya tanpa ada yang protes.”
Hujan mulai berkurang, tapi aku tidak bergerak dari tempat duduk.
“Setelah keluar dari sekolah, susah cari kerja. Mana ada tempat yang mau nerima guru dengan reputasi kayak gitu. Akhirnya aku belajar potong rambut sama mbak-mbak di salon deket rumah. Modal nekat, buka salon sendiri di gang ini.”
Kayla mengambil sisir dan mulai merapikan peralatan kerjanya. “Awal-awalnya gimana? Susah banget. Tetangga pada bisik-bisik. Pelanggan pertama cuma satu dua orang yang kasihan. Ada yang sengaja datang cuma buat nanya-nanya, bukan buat potong rambut. Penasaran sama cerita yang mereka denger.”
Dia mulai mengatur botol-botol di raknya. “Tapi lama-lama… orang ngeliat hasil kerjaku. Rambut yang aku potong rapi. Hargaku murah. Pelayananku baik. Yang penting aku konsisten.”
“Sekarang udah agak stabil. Pelanggan tetap ada sepuluh-an. Nggak kaya dulu waktu jadi guru, tapi cukup buat hidup. Dan yang paling penting… aku nggak bergantung sama siapa-siapa lagi. Aku nggak perlu minta izin ke kepala sekolah, nggak perlu takut dipecat gara-gara gosip.”
Kayla diam sebentar, menatap cermin di depannya. “Kadang aku mikir, mungkin ini jalan yang memang harus aku lalui. Buat ngajarin aku bahwa hidup itu nggak selalu sesuai rencana.”
“Sakitnya karena… aku kehilangan kepercayaan. Ke orang lain, ke diri sendiri. Aku jadi takut deket sama laki-laki. Takut percaya lagi.”
Dia bangkit dari kursi. “Kemarin ada tukang ojek yang sering nganter pelanggan ke sini. Dia baik, sering ngobrol. Tapi begitu dia mulai ngajak ketemuan di luar, aku langsung mundur. Aku takut dia cuma pengen… ya itu, video-video yang mungkin masih beredar.”
“Pernah kepikiran pindah dari Samarinda?”
“Pernah. Tapi ke mana? Keluargaku di sini. Dan lagian, lari juga nggak menyelesaikan masalah. Aku memilih bertahan dan buktiin bahwa aku masih bisa hidup dengan kepala tegak.”
Hujan di luar mulai mereda. Suara tetesan air dari ateng salon terdengar seperti musik pelan.
“Pengen nabung, buka salon yang lebih besar. Atau balik jadi guru lagi, kalau memungkinkan. Di TK lain, atau les privat. Aku masih suka anak-anak. Masih inget gimana caranya ngajarin mereka baca tulis.”
Kayla menatap ke luar jendela. “Yang penting sekarang, aku punya tempat ini. Tempat di mana aku bisa jadi diri sendiri. Tempat di mana orang-orang datang bukan buat ngehakimi, tapi buat dipotong rambutnya dan pulang dengan perasaan lebih baik.”
“Pernah ketemu Doni lagi?”
“Pernah, pas di Mall Besar. Dia sama istri barunya—ternyata dia nikah sama cewe yang dulu jadi selingkuhannya. Aku cuma lewat aja, dia yang manggil. Minta maaf katanya.”
Kayla tertawa pahit. “Lucu kan? Dia minta maaf pas hidupnya udah enak. Pas aku yang udah struggle bertahun-tahun. Aku cuma bilang, ‘Udah lah, Don. Yang penting kamu bahagia.’ Terus aku pergi.”
“Marah itu cuma ngeracunin diri sendiri. Dia udah dapet karma-nya sendiri—hidup dengan rasa bersalah. Aku? Aku udah bebas dari dia.”
Kayla menatap keluar jendela. Hujan sudah hampir berhenti.
“Tapi aku belajar, Kak. Bahwa hidup ini nggak berhenti gara-gara satu kesalahan. Atau satu orang jahat. Aku masih bisa potong rambut dengan bagus. Aku masih bisa bikin orang senang dengan hasil kerjaku. Aku masih bisa bangun pagi dan nggak malu sama cermin.”
“Ada rencana ke depan?”
“Kayak yang aku bilang tadi. Pengen nabung, buka salon yang lebih besar. Atau balik jadi guru lagi, kalau memungkinkan. Aku masih suka anak-anak. Dan mungkin… suatu hari nanti, kalau ada laki-laki yang bisa nerima masa laluku, ya syukur. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Aku udah belajar bahagia sama diri sendiri.”
Hujan berhenti. Jalanan masih basah, tapi sudah bisa dilalui.
Aku bersiap pergi, tapi Kayla berkata, “Makasih ya, udah mau dengerin. Jarang ada orang yang mau dengerin tanpa judge.” kedua kalinya aku mendengarkan kalimat itu diucapkan kepadaku.
Keluar dari salon kecil itu, aku berpikir tentang betapa kejamnya dunia terhadap perempuan seperti Kayla. Mereka yang menjadi korban, tapi harus menanggung malu. Mereka yang dikhianati, tapi harus meminta maaf pada dunia.
Tapi aku juga berpikir tentang kekuatan Kayla. Caranya bangkit dari keterpurukan. Caranya membangun hidupnya kembali dengan tangannya sendiri. Dan caranya tetap percaya bahwa dia layak untuk memulai lagi, meski tanpa harus bergantung pada siapa pun.