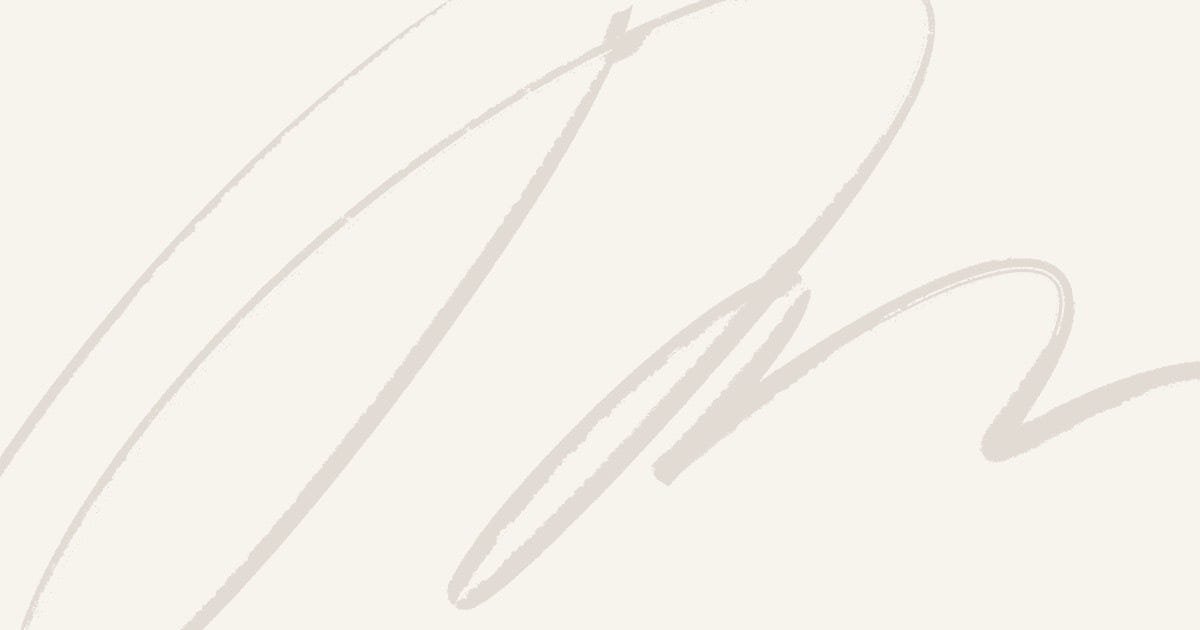Harapan Baik, Kabar Baik, Nasib Baik | by hsellyzha | Jul, 2025

Aku suka membahas kematin, tetapi jika ia benar-benar nyata di depan mata, rupanya aku ciut juga. Dulu waktu mengaji, Pak Ustadz menceritakan bahwa ketika malam sebelum kematian tiba, kita akan kedinginan hingga menggigil. Suasana saat kedatangan malaikat Izrail itu juga terasa menegangkan. Ia akan menggedor pintu dengan keras jika amalmu sedikit atau mengetuk pintu pelan sambil mengucap salam jika amalmu banyak.
Tapi, yang tak pernah diceritakan adalah “Apa yang terakhir orang pikirkan ketika dia akan meninggal?” “Apakah orang yang akan meninggal itu tau kalau dia akan meninggal?”
Aku tidak bertanya pada Mama, apa yang dipikirkannya sebelum ia benar-benar tidak bernafas. Aku hanya merangkulnya sembari melafalkan “Allah” tanpa henti. Mungkin saat itu Mama memikirkanku, sebab matanya terarah padaku sampai aku harus mengusap wajahnya agar ia terpejam.
Setiap kali ada yang meninggal, orang-orang cenderung membahas hal-hal yang dianggap sebagai tanda perpisahan dari orang itu. Aku juga menemukannya, tapi tidak benar-benar yakin apakah itu sebuah tanda.
Sebelum Dif meninggal, ia ingin menghabiskan banyak waktu denganku. Bahkan dia mau ku ajak berkunjung ke rumah, hal yang tidak pernah mau ia lakukan sebelumnya karena suatu hal. Ia juga pernah mengutarakan keinginannya bahwa dia ingin sekali lebih dekat dengan Tuhan. Sungguh aku tidak mengira jika itu adalah sebuah tanda.
Bunuh Diri, dan Kenapa Orang Bisa Bunuh Diri
Dulu aku ingin sekali bunuh diri. Banyak yang berpikir bahwa orang bunuh diri karena sedang menghadapi cobaan sulit, atau tertekan, atau tidak sanggup menghadapi nasib sial. Mungkin sebenarnya bukan itu alasannya. Hal yang paling ingin membuatku bunuh diri adalah rasa tidak nyaman dan benci terhadap diri sendiri.
Perasaan seperti “kenapa sih aku terlahir begini?”, “kenapa sih aku melakukan hal bodoh ini?”, “kenapa sih aku tidak bisa melakukan perubahan seperti ini?”, dan sebagainya. Perasaan bahwa aku tidak berguna, dan tidak ada gunanya di dunia, adalah motivasi terbesar untuk aku mengambil pisau dan menggoreskannya.
Untungnya, aku terlalu pengecut untuk benar-benar melakukan itu. Aku hanya berani membenturkan kepala, menjambak rambut, atau menggigit pergelangan tangan. Lucunya, orang-orang waras menyalahkan hal itu, menyuruh untuk bersyukur dan berpikir positif tanpa mengerti bahwa terjebak dalam pikiran sendiri dan kehilangan kontrol untuk mengendalikannya adalah hal yang sangat menyakitkan.
Bayangkan saja, kepalamu tidak pernah berhenti berisik, lalu tiba-tiba memunculkan memori-memori buruk, lalu dadamu mulai sesak dan kamu menangis. Tapi dirimu sendiri bahkan tidak mengerti kenapa kamu menangis, dan tangis itu tidak bisa kamu hentikan sampai ada distraksi lain. Bagi orang yang tidak punya support sistem yang baik, distraksi lain itulah yang seringkali berbentuk tindakan self harm. Sebab luka fisik itu menghentikan kemelut di kepala yang tidak bisa kita kontrol, luka fisik itu sakit tapi terasa seperti obat untuk tenang.
Meski tidak bisa juga dibenarkan, tapi bagiku orang yang bunuh diri adalah orang yang berani. Sebab mereka tanpa gentar meminta kematian, sedang aku sendiri tidak cukup berani melakukannya.
Ada 3 hal yang menyentuh perasaanku dan membuatku berhenti berpikir untuk bunuh diri. Pertama, salah satu bahasan dalam ngaji filsafat, “Banyak orang yang berani mati, tapi tidak banyak yang berani hidup. Maka jadilah bagian yang sedikit itu. Sebab kemenangan bukan ketika kamu mencapai banyak hal, tapi ketika kamu bisa bertahan”.
Kedua, ucapan dari seorang laki-laki yang pernah dekat denganku, “Jangan selalu su’udzon sama Tuhan. Mungkin saja Tuhan sedang menguatkanmu untuk siap menghadapi hal indah yang besar”. Dia memang anak rohis, maka nasihatnya cenderung berbau keislaman. Tapi yang membuat kalimat ini membekas dibanding nasihat keislaman lainnya, karena saat itu aku tersadar bahwa aku memang selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan. Aku memandang hidupku sebagai sebuah pemberian yang tidak pernah aku inginkan, alih-alih memandangnya sebagai hal yang bisa aku kendalikan.
Ketiga, ucapan yang aku dengar di Youtube entah dari channel apa, katanya begini “Hak paling dasar yang dimiliki manusia itu adalah hak hidup, maka jangan merebut hak dirimu sendiri untuk hidup, untuk bermimpi, dan untuk mendapatkan banyak hal baik”.
Setelah itu, aku berusaha keras untuk tidak menyakiti diriku sendiri. Sebab, aku kasihan pada diri sendiri jika ia harus berhenti mendapat kemungkinan-kemungkinan baik sebab ku rampas hak hidupnya. Aku ingin bertahan, karena dengan bertahan, aku menang dari berbagai rasa sakit dan nasib sial.
Meski tidak mudah, meski sesekali aku masih suka menangis, meski sesekali emosiku meledak, meski orang-orang masih mengira aku sinis, meski harus merogoh gocek sedikit lagi untuk ke psikolog. Tapi, sama dengan semua makhluk hidup di dunia, bahwa diriku layak disayangi, terlebih oleh diri sendiri
Kematian di Depan Mata
Pengalaman ini dimulai sejak aku merasa leherku kaku, ada benjolan kecil di sana, dan terasa sakit setiap kali aku tertawa atau makan. Seperti kebanyakan orang denial, aku mengira sakit itu akan sembuh dengan sendirinya. Mungkin itu karena salah bantal, pikirku.
Setelah hampir 3 bulan bertahan, sakit itu tidak juga sembuh malah justru semakin sakit. Aku meminta temanku untuk periksa di sebuah rumah sakit swasta. Kata temanku, itu adalah rumah sakit yang bagus dengan pelayanan yang baik. Memang benar, di sana pelayanannya ramah, cepat, dan dokternya sangat komunikatif.
Hasil pemeriksaan saat itu aku terkena infeksi pembengkakan kelenjar getah bening. Kata dokter, ini bukan penyakit, tapi tanda bahwa tubuhku sudah tidak bisa melawan potensi penyakit yang sedang menyerang. “Kelenjar getah bening itu ibarat polisi Mbak, polisi itu menangkap penjahat-penjahat yang masuk ke tubuh kita. Kalau penjahatnya kecil mudah ditangkap kelenjar getah bening itu akan mengecil sendiri. Tapi kalau penjahatnya banyak, polisinya kalah. Nah, yang Mbak alami ini, polisinya kalah, jadi dia membengkak. Tapi kita tidak tahu penjahatnya apa kalau tidak dioperasi”, begitu dokternya menjelaskan.
Saat itu aku diminta untuk melakukan rangkaian pemeriksaan lain yaitu cek darah dan USG. Itu pertama kalinya aku melakukan USG yang merupakan pemeriksaan paling seru dari rangkaian pemeriksaan lainnya. Aku berbaring di bangkar yang nyaman, dengan layar kecil tergantung di depannya. Mula-mula dokter radiologi itu mengoleskan cairan lengket yang terasa dingin, lalu dia mulai menggerakkan alatnya, dan aku bisa melihat bagian dalam leherku di layar. Aku tidak paham sama sekali, aku hanya melihat layar hitam, sedikit abu-abu, sedikit putih, lalu ada bulatan seperti kerikil di sana. “Itu apa Dok?”, tanyaku. “Itu isi benjolannya Mbak,” jawab dokternya singkat.
Selepas rangkaian pemeriksaan itu, kami pulang, dan aku mulai menangis di lobi rumah sakit. Temanku jelas bingung. “Nggak papa Ly, kamu pasti sembuh kok,” katanya menenangkan. “Bukan Wi, aku bukan nangis karena sakitnya, ini hampir 1,5 juta habis dalam sekejap mata Wi,” tangisku. Memang saat itu BPJS-ku belum aktif, jadi aku periksa dengan biaya mandiri. Rp. 130,000 untuk periksa dokter, Rp. 500,000 untuk USG, Rp. 120,000 untuk cek darah, dan Rp. 500,000 untuk tebus obat. Setengah gajiku habis, aku bahkan belum makan saat itu, untungnya Tanteku berbaik hati untuk menyumbang.
Ku pikir, rasa sakit ini tidak akan mengganggu pikiranku. Memangnya kenapa kalau aku mati, bukankah kematian adalah satu-satunya kepastian yang kita miliki. Lagipula, siapa yang akan menangis jika aku mati? Justru bagus kan, keluargaku tidak akan kerepotan lagi.
Tapi rupanya keputusan dokter bahwa aku harus operasi tetap membawa kecemasan bagiku. Aku menghadapi malam-malam penuh ketakutan setelahnya. Rasanya, sebentar lagi akan ada gedoran pintu atau salam dari malaikat Izrail. Aku bahkan tidak bisa tidur, dan terus menyalakan youtube agar kamar tidak sepi.
Sampai akhirnya tiba jadwal operasi. Untuk pertama kalinya aku melakukan pemeriksaan jantung, foto rontgen, menginap di rumah sakit, dan diinfus. Tapi rangkaian pemeriksaan itu ternyata tidak semenyeramkan yang ku bayangkan.
Aku tidak perlu ditusuk berkali-kali untuk diinfus, tidak sakit juga karena cairan infus membuatku segar, aku jadi punya banyak waktu untuk baca buku, dan yang paling aku suka…. makanan rumah sakit itu enak.
Semalam aku diminta berpuasa sebelum besoknya mulai dioperasi. Aku terbaring di atas bangkar, lalu suster mendorongnya, nyaman sekali. Kami berhenti di sebuah ruang transit kecil. Di situ suster memintaku untuk berganti pakaian. Aku memakai jubah biru yang biasa dipakai pasien di sinetron-sinetron. Aku terbaring di bangkar lagi, lalu suster membawaku melewati lorong menuju ruang operasi. Tau apa yang ku pikirkan saat itu? Aku seperti sedang syuting film hidayah di Indosiar. Seperti pemeran antagonis yang kena azab.
Sampai ruang operasi itu dibuka, yang menyambutku pertama kali adalah hawa dingin. Mungkin ada 2–3 AC di sana, aku tidak tau. Dokter, suster, atau mungkin anak koas mengelilingi bangkar yang ku tiduri. Aku mulai dipasangi alat bantu nafas dan selang-selang yang entah apa fungsinya. “Kalau ngantuk jangan dilawan, tidur aja ya,” kata suster yang menyuntikkan sesuatu di selang tanganku. Aku hanya mengangguk dan perlahan kesadaranku hilang.
Harapan Baik, Kabar Baik, Nasib Baik
“Kalau aku mati, jangan buat desain turut berduka cita yang jelek ya! Kamu harus buat yang keren, berwarna, ala-ala retro atau futuristik gitu juga boleh,” kataku pada seorang teman. “Iya, ntar gua endorse kain kafan sekalian, sama buat video jedag-jedug,” jawabnya.
Setelah selamat dari ruang operasi, hidup terasa lebih berharga. Keinginan untuk makan dengan baik dan berolahraga lebih tinggi dari sebelumnya meskipun belum konsisten. Aku mulai merasa bahwa kebersamaan dengan orang-orang di sekelilingku begitu besar maknanya. Mungkin mereka tidak menangis ketika aku mati, tapi mereka begitu menyayangiku selama aku hidup. Meskipun rasa sayangnya berbentuk omelan atau lelucon, tapi mereka tetap di sana, tetap membantuku, tetap berharap aku hidup.
Sekarang aku sakit lagi, benjolan-benjolan masih tumbuh di sekitar leher. Aku akan menjalani operasi kedua, dan rangkaian pengobatan yang panjang. Ke rumah sakit, bertemu dokter, minum obat, akan menjadi rutinitas setelah ini.
Tapi, rangkaian pemeriksaan kali ini tidak terasa menakutkan seperti sebelumya. Mungkin kita hanya perlu terbiasa untuk menghadapi rasa sakit dan ketidak nyamanan. Sampai kita menyadari betapa hebat dan kuat diri kita, dan semua itu terasa biasa saja.
Saya punya harapan baik untuk tetap hidup, untuk menyelesaikan banyak kebodohan yang saya lakukan, untuk mengupayakan mimpiku sendiri, dan untuk melihat kejutan-kejutan luar biasa lainnya yang mungkin telah Tuhan siapkan.
Semoga harapan baik membawa kabar baik. Terima kasih juga untuk teman-teman dan keluarga yang juga terus mengirim doa baik. Semoga kebaikan terus bersama kita semua, dalam wujud nasib baik.
TABIK!